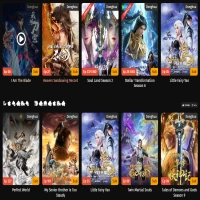Pojokan 209 : Hidup yang Mati

Kang Marbawi
Pojokan 209
Mati
Kau datang ke sini tanpa belas kasihan, padahal kau hidup, makhluk yang hidup.
Apa kau sudah mati dalam kejagaanmu. Mati sendiri, atau dimatikan atau sengaja mati?
Menjadi hidup hanya untuk kulit dan menumbuhkan daging. Juga syahwat!
Imaginasi untuk mengejar kesenangan daging, syahwat dan kuasa menjadikanmu, mati. Kau dan aku hidup dalam matinya nurani dan welas asih. Dimula dari tumpulnya kepekaan dan tumbuh kembangnya kebebalan rasa. Merambah pada membatunya pikiran kritis pada ketimpangan.
Bertumbuh untuk mengejar kedudukan-kuasa menguasai. Kedudukan yang direbuti dan diukupi keserakahan-rakus! Hingga tak berani untuk berlaku benar. Padahal konon kata orang Jerman berkumis tebal, Friedrich Nietzsche, seseorang yang hidup harus memiliki keberanian. Keberanian untuk hidup penuh kebenaran. Hanya para nabi dan rasul yang hidup penuh kebenaran juga keberanian.
Kita sudah mati, karena takut untuk berani hidup benar. Melumpuhkan keberanian untuk bersuara dan menyuarakan apa kata nurani.
Semua dirundung takut. Takut tak tercukupi, takut tak dapat, takut atasan, takut tak berkuasa dan utopi ketakutan lainnya. Ketakutan yang merampok beningnya nurani. Mengejar kemaruk harta, tahta, dan angkara. Dan takut akan terputusnya simbiosis mutual dari lakon dengan patron. Ketakutan yang menghalau welas asih dan kepekaan. Menyingkirkan rasa malu. Mencampakkan kepatutan.
Kau dan aku mati!
Kehidupan hanya untuk pemenuhan syahwat. Bahkan diperjuangkan dengan segala cara. Lebel harta dan jabatan kadang menjadi kafan dari kematian jiwa. Menjadi jubah dari perturutan syahwat dan kekuasaan. Dipermatai keserakahan dan penindasan. Dibumbui penyelewengan, pun manipulasi. Tak luput hukum pun dipecundangi. Demi kelanggengan atas kuasa dan harta. Hingga menyungkurkan susila dan moral.
Seperti matinya moral seorang wasit ajang demokrasi. Dia mati karena perturutan syahwat. Demi isi “CD”, menabrak susila, dan kepatutan, yang bertumpu pada aji mumpung kuasa. Dan melayangnya rasa malu.
Yang seperti ini, tak hanya itu. Hanya tak muncrat di media sosial dan panggung lakonnya. Dikubur untuk tak menjadi tontonan aib. Sebab kita pun punya aib. Maka ditutupi, sembunyi dan disunyikan. Bahkan dibungkam!
Yang mati ruhaninya pun merebak pada yang tak berharta dan tak menjabat. Kematian yang menjambret jiwa-jiwa ketulusan. Semua dinominalkan dan hanya untuk keuntungan. Merebak dalam amuk massa dan anarkis. Welas asih tinggal kenangan. Menjelma dalam keberingasan.
Pada akhirnya, kulit ini tinggal menunggu waktu untuk dipendam. Entah diingat atau tidak. Disitulah sebenarnya hidup. Hidup ketika diingat manusia yang mati dan atau hidup nuraninya di muka bumi. Diingatpun pada tingkah kulit yang ciut untuk berbuat patut. Dikenang atas ketakpatutan laku moral, watak dan gerak hidup.
Maka untuk menjadi hidup dalam kehidupan. Peka-kan rasa. Hidupkan nurani dari kematian. Rasailah disegala yang sakit, tertindas, marginal, terpinggirkan dan terabaikan. Reguklah rasa penyakit yang sakit, terlihat oleh mata dan dirasai hati. Dari segala penyakit jasmani yang di kulit, di dalam kulit, di tulang, di sumsum, di darah dan di jiwanya. Datangi rumah sakit.
Kita bisa mengasah kepekaan, untuk bangun dari kematian. Untuk mereguk rasa welas asih kepada sesama. Untuk merasai sengsara dan derita. Dan mengentaskannya. Kuasa dan harta bisa menjadi alat. Asal dijalankan dengan benar dan berani. Dijiwai oleh kegelisahan atas ketimpangan dan ketidakadilan. Dihiasi oleh moral dan etika.
Daging ini, syahwat ini perlu dihidupi. Dihidupi rasa malu dan etika. diinsyafi dengan kebenaran dan keberanian, untuk mengentaskan sesama yang hidup. Dalam kehidupan yang penuh welas asih. Juga kesederhanaan. Agar tidak mati hati. (Kang Marbawi,040624)