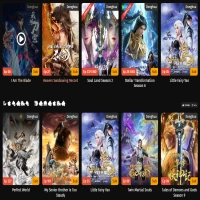Mengelola Sumber Daya Alam untuk Masa Depan Berkelanjutan: Nature-Based vs Human-Based ?

Penulis: Aziz Akbar Mukasyaf, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
Afiliasi: Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dalam lanskap pembangunan modern yang kini semakin kompleks, pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci strategis untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Sumber daya alam, baik yang terbarukan seperti air, udara, dan hutan, maupun yang tidak terbarukan seperti mineral dan energi fosil, merupakan fondasi kehidupan yang menopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Secara umum, pengelolaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pemanfaatan, konservasi, hingga restorasi sumber daya tersebut dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pemanfaatan hari ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati manfaat yang sama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam harus dilihat tidak hanya dari segi efisiensi ekonomi, tetapi juga dari dimensi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan (WCED, 1987).
Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam memiliki dua pendekatan utama yang berkembang: pendekatan berbasis alam (nature-based management) dan pendekatan berbasis manusia (human-based management). Pendekatan nature-based secara umum melihat sesuatu hal yang berhubungan dengan interaksi manusia dari cara memanfaatkan proses dan ekosistem alami. Sehingga nantinya diharapakan pendekatan tersebut dapat merespons tantangan lingkungan dan sosial yang terjadi. Contohnya: 1) pelestarian mangrove sebagai benteng alami terhadap abrasi dan banjir, 2) restorasi lahan melalui agroforestri, dan 3) hingga pengelolaan air dengan sistem alami seperti kolam retensi dan taman hujan. Pendekatan ini mempercayai bahwa alam memiliki mekanisme regulasi dan resilien yang tinggi, dan jika dikelola secara bijak, dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan (Seddon et al., 2020). Di sisi lain, pendekatan human-based yaitu menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam sebuah ekosistem. Manusia yang berperan penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya dengan menggunakan teknologi dan kebijakan dalam merespons tantangan lingkungan dan sosial yang terjadi. Human-based management sebenarnya bisa menguntungkan bagi alam atau lingkungan. Akan tetapi ada syarat penting yang harus dilakukan, yaitu pengelolaannya harus berorientasi jangka panjang, berbasis ilmu pengetahuan, serta menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability). Contoh dari pendekatan ini adalah 1) Rehabilitasi Hutan dengan Teknologi Modern, dimana manusia menanam pohon dengan teknik agroforestri atau drone penanaman bibit, sehingga mempercepat pemulihan hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Teknologi Irigasi Hemat Air, yaitu sistem irigasi tetes atau smart irrigation mengurangi penggunaan air berlebihan pada lahan pertanian, sehingga cadangan air tanah tetap terjaga, 3) Pembangkit Energi Terbarukan, Pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau air yang dikelola dengan baik mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan energi fosil, dan 4) Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Circular Economy, sistem daur ulang modern dan pemanfaatan biogas dari limbah organik bisa mengurangi polusi dan menghasilkan energi bersih.
BACA JUGA: Pojokan 263: Juara Doa
Secara umum, kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan nature-based memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam aspek keberlanjutan jangka panjang. Ia cenderung lebih ramah lingkungan, memelihara keanekaragaman hayati, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, pendekatan ini sering kali lebih hemat biaya dalam jangka panjang karena tidak memerlukan infrastruktur besar dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Namun demikian, implementasinya memerlukan waktu yang panjang untuk menunjukkan hasil, serta sangat bergantung pada kondisi iklim dan dukungan sosial dari komunitas (dalam hal ini manusia). Sebaliknya, pendekatan human-based memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan skala implementasi (tentunya untuk kesejahteraan manusia). Dengan teknologi dan kebijakan yang tepat, manusia dapat mengubah bentang alam secara masif untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan perumahan. Namun, pendekatan human-based ini juga rentan menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya ekosistem alami, dan sering kali mengabaikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, dampaknya terhadap komunitas lokal, seperti konflik lahan atau marginalisasi masyarakat adat, menjadi persoalan serius yang terus mengemuka (Walhi, 2023).
Namun,apabila dibandingkan secara kritis, pendekatan nature-based dan human-based bukanlah pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya dapat saling melengkapi jika dipadukan secara bijaksana dalam kerangka pengelolaan terpadu. Misalnya, dalam pengelolaan daerah aliran sungai, pendekatan nature-based dapat diterapkan dengan menanam kembali vegetasi hutan lindung (berdasarkan kesesuaian tapak), sementara pendekatan human-based digunakan dalam penguatan infrastruktur irigasi dan pemantauan debit air dengan teknologi digital. Dalam era perubahan iklim dan tekanan global terhadap sumber daya alam, kombinasi keduanya menjadi semakin relevan. Konsep seperti eco-engineering dan smart green infrastructure menjadi contoh bagaimana teknologi dan alam bisa bersinergi, bukan saling bertentangan.
Terlebih lagi, sebetulnya Human-based management bukanlah pendekatan yang harus ditolak, melainkan perlu dikaji ulang dan diletakkan dalam kerangka etik dan batasan ekologis yang tegas. Dalam realitas dunia dengan populasi manusia yang terus bertambah—diperkirakan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 (UN, 2019)—tuntutan akan energi, pangan, dan ruang hidup tidak dapat dihindari. Di sinilah letak tantangan human-based management: bagaimana teknologi dan intervensi manusia dapat menjawab kebutuhan tersebut tanpa merusak daya dukung bumi dan sumberdaya alam yang ada.
Hal yang perlu dan penting untuk dipahami dan kita sadari bersama adalah bahwa pendekatan human-based tidak hanya berarti pembangunan fisik atau industrialisasi, melainkan juga mencakup sistem kebijakan, sistem informasi, hingga mekanisme pengambilan keputusan yang dikendalikan manusia. Oleh sebab itu, batas-batas implementasi perlu ditetapkan secara multidimensi, antara lain:
BACA JUGA: TKA Sebagai Sarana Menumbuhkan Tanggung Jawab Belajar
1) Batas Ekologis (Planetary Boundaries)
Pengelolaan tidak boleh melampaui ambang batas ekosistem. Seperti yang dikemukakan oleh Rockström et al. (2009), terdapat sembilan batas ekologis global (seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, siklus nitrogen-fosfor) yang tidak boleh dilewati jika ingin menghindari keruntuhan sistem bumi;
2) Batas Sosial
Pendekatan human-based juga harus mempertimbangkan keadilan sosial. Infrastruktur yang dibangun tidak boleh mengorbankan masyarakat adat, meminggirkan perempuan, atau menyebabkan ketimpangan spasial antara kota dan desa. Pendekatan ini harus menjamin hak masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber daya lainnya;
3) Batas Demokratis
Dalam banyak kasus, pendekatan manusia cenderung teknokratis dan top-down. Maka, batas ini menuntut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi data, dan akuntabilitas pemerintah dalam setiap proyek sumber daya alam;
4) Batas Teknologi yang Bijak
Tidak semua teknologi adalah solusi. Ada saatnya penggunaan teknologi justru menciptakan dampak baru. Oleh karena itu, human-based management perlu mengadopsi prinsip appropriate technology—yakni teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal, tidak merusak alam, dan dapat dikelola oleh komunitas.