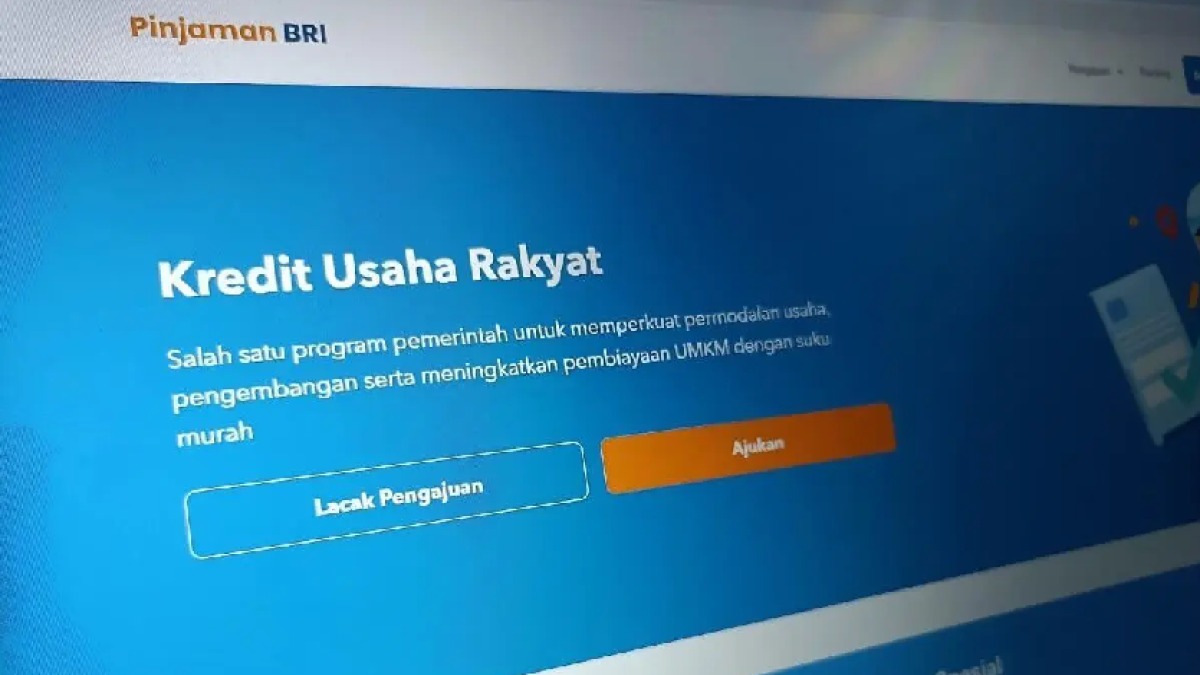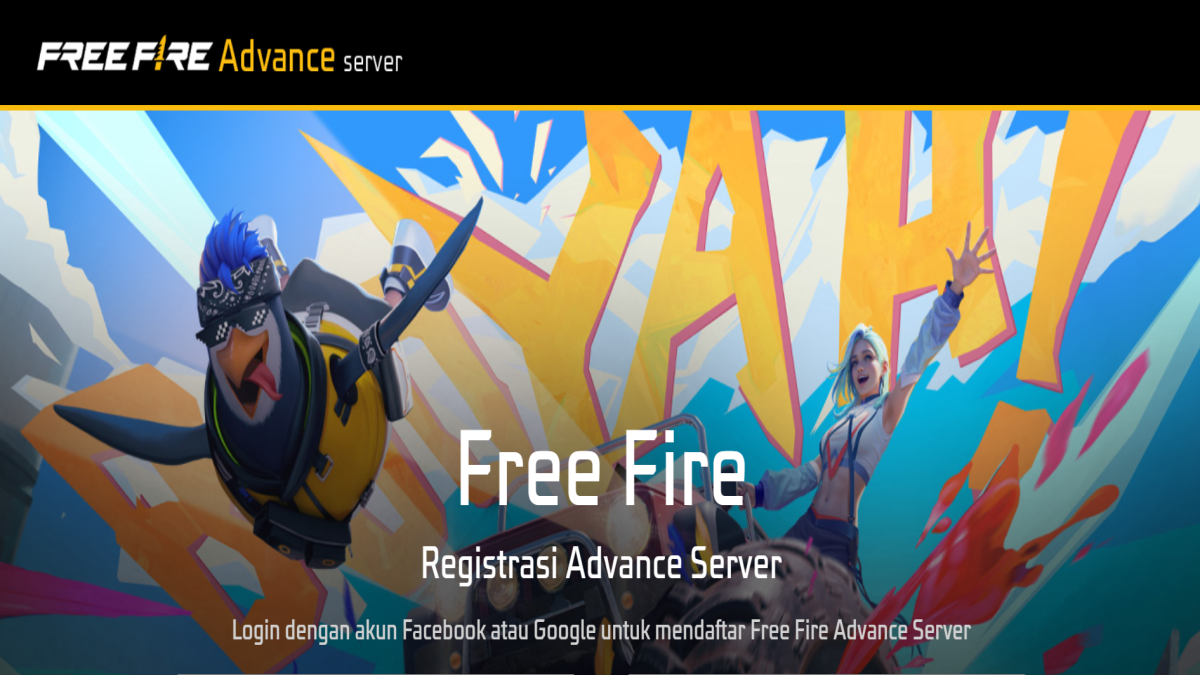Dia bukan tokoh politik utama di tahun 1948. Dia juga tak pernah membanggakan nasabnya. Tapi dia menjadi incaran dan dicari Belanda. Sebab dia membawa selembar kain dua warna.
“Kain ini, tidak boleh jatuh ke tangan musuh”.
Demikian pesan Sang Proklamator kepada Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad al-Muthahar alias Husein Muthahar alias Kak Mutahar, ajudannya Soekarno.
Pesan diatas sebelum Bung Karno di tangkap dan diasingkan ke Berastagi-Parapat Sumatra Utara lalu dipindahkan ke Bangka tahun 1949.
Muthahar -yang juga pendiri Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dan Pandu Pramuka (Praja Muda Karana) sadar, selembar kain ini adalah, marwah bangsa.
Simbol negara yang dijahit sendiri oleh tangan Ibu Fatmawati ini, tidak boleh jatuh kepada penjajah Belanda. Kain yang kemudian jahitannya dibuka dibantu Pernadinta itu, harus dijaga dengan nyawanya.
Muthahar menyelempangkan potongan kain berwarna merah di pinggangnya. Sementara yang putih di masukan ke dalam tas. Alibi untuk mengelabui Belanda, jika menangkapnya, bahwa itu sekedar kain biasa. Bukan Sang Saka Merah Putih yang sakti dan bertuah.
Ketakutan dan kecemasaannya semakin memuncak. Tak karuan akibat agresi II Belanda. Muthahar pun tertangkap di Semarang setelah Yogyakarta direbut Van Mook. Tapi Sang Dwiwarna selamat. Belanda tidak tahu, maka tak merampasnya.
“Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi. Dalam keadaan apa pun, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera ini dengan nyawamu”, ucap Soekarno kepada Muthahar. Dalam
“Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat”, karya Cindy Adams.
Muthahar terbakar patriotisme, untuk membela dan menjaga dengan segenap jiwa raga. Walau harus mendekam dalam penjara Belanda dengan segala siksaan dan derita. Sang Merah Putih selamat.
Hingga akhirnya, diahkir Juni 1949, dia menerima surat dari Sang Putra Fajar. Melalui surat itu, dia diminta agar Sang Saka Merah Putih dititipkan kepada Soedjono untuk dibawa ke Bangka Belitung.
Sang Dwiwarna sendiri lahir dari jahitan tangan Ibu Fatmawati dua minggu sebelum kelahiran Guntur Soekarno Putra, pada Oktober 1944.
Kain katun merah putih itu berasal dari pemberian Hitoshi Shimizu, pemimpin barisan Propaganda Jepang, Gerakan Tiga A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Shimizu bersimpati kepada Indonesia.
Shimizu sendiri mendapatkan kain katun untuk bendera tersebut dari salah satu pejabat Jepang yang mengepalai Gudang di daerah Pintu Air, depan bioskop Capitol, Jakarta Pusat.
Adalah Chairul Basri yang diminta Ibu Fatmawati untuk meminta ke Shimizu. Karena waktu itu hanya ada karung goni yang tebal dan tidak bisa dijadikan bendera. Cerita ini dikisah Abraham Panumbangan dalam “The Uncensored of Bung Karno”.
Setahun kemudian, bendera itu, dikibarkan di hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.
Sejak jaman kerajaan di nusantara, Sang Dwiwarna telah berkibar. Kerajaan Singosari, Majapahit, pejuang Aceh, Sisingamangaraja XII, Pangeran Dipenogoro, Raja Alung Palakka dari Bone telah mengibarkan sang Waromporang-bendera Merah Putih- simbol kekuatan dan perlawanan.
Ada tuah dalam selembar kain itu. Tuah yang lahir dari sejarah, budaya, air mata, nyawa, harta, penderitaan, perbudakan, dan perlawanan yang tak hingga dari rakyat Indonesia. Demi simbol suci bangsa.
Mewujud dalam kesaktian untuk bisa menyatukan dan menggerakkan rakyat demi berkibarnya bendera Merah Putih. Dimanapun, kapanpun hingga akhir jaman.
Sang Saka Merah Putih, adalah metamorfosis darah dan tulang dari jutaan rakyat Indonesia yang rela berkalang tanah. Mengorbankan dan dikorban serta menjadi korban demi kedaulatan, kemerdekaan dan berkibarnya Merah Putih.
Sang Dwiwarna adalah kedaulatan yang harus dijaga dan dibela. Sang Saka adalah wujud dari cita luhur persatuan, kedaulatan, kejayaan dan kemakmuran bangsa. Di Merah Putih, wujud kebanggan menjadi Bangsa Indonesia.
Cita itu, belum terwujud penuh. Belum diresapi makna dan cita perjuangannya. Sebab sang Dwiwarna hanya diukupi disetiap upacara. Hanya itu!
Cita Sang Saka Merah Putih belum nampak dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Cita yang dirusak oleh laku koruptif, etika yang tersungkur, kekerasan yang menjadi budaya dan hukum yang dipecundangi.
Sang Dwiwarna melambai marah, pada kedaulatan yang digadai, terjual, atau sengaja dijual. Oleh siapa dan kenapa, tak pernah tahu. Sebab kita sama-sama tahu. Mungkin kita perlu berjuang lagi untuk Merah Putih. Seperti Kak Muthahar. (Kang Marbawi, 280724).