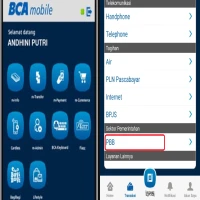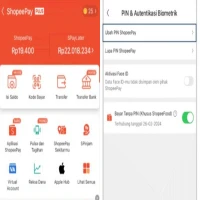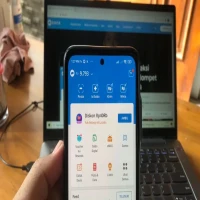Pojokan 235: Sindrom Müller-Lyer

Kang Marbawi.
Lain dulu, lain sekarang. Dulu orang bicara tak pernah mengada-ngada dan tak perlu mengada-ngada. Pendengar percaya, karena yang dibicarakan sesuai dengan laku sang pembicara.
Tengok saja apa kata Maha Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa-nya. Atau Mpu Tantular dengan “Bhineka Tunggal Ika- Tan Hana Dharma Mang Rwa”. Itu jaman kerajaan.
Petuah-petuah Moh. Hatta, Agus Salim, Ir. Soekarno dan tokoh-tokoh nasional lainnya, pun satu kata dan perbuatan. Tak melenceng sedikitpun seperti ukuran lantai granit, simetris, tidak bengkok, apalagi bertolakbelakang. Presisi kata orang teknik.
Lain lagi cerita jaman kiwari. Satu kata yang keluar dari seseorang, kadang tak terkoneksi dengan kenyataan yang ada. Hanya mencari sensasi. Hasilnya, kata yang menyembur itu (baik melalui postingan media sosial/medsos), bisa dikomentari menjadi puluhan kata. Dan belum tentu benar komentarnya dengan fakta.
BACA JUGA: Pemberian Fatwa Haram Sound Horeg oleh Majelis Ulama Indonesia
Kini, perangkat komunikasi sudah beragam. Melalui medsos; WhatsApp, Facebook, blog pribadi, SnapChat, Twitter, YouTube, resonansinya melebihi gemuruh petir. Akibatnya fakta dan kebenaran tereduksi, bagai fatamorgana genangan air ditengah padang pasir.
Melahirkan ilusi optik. Di medsos terjadi Ilusi, menjadi viral lebih penting dibanding dengan kebenaran dan fakta itu sendiri. Mengabaikan kualitas informasi dan etika. Hingga muncul adagium; “no viral, no justice”.
Sang pengadil atau penegak hukum, seolah dipecundangi oleh viralitas. Tergopoh-gopoh merespon kasus yang telah viral. Bagai orang tua yang berusaha menolong anaknya yang kesedak atau kepleset kulit pisang.
Padahal tidak semua yang viral, belum tentu benar. Namun masyarakat kadung percaya yang tranding topik adalah yang valid Dijaman medsos, kita (masyarakat) dikondisikan untuk abai terhadap verifikasi berita. Apapun yang ada di medsos, apalagi yang viral, sering kali tak dipertanyakan lagi kebenaran dan kredibilitasnya.
BACA JUGA: Pojokan 261 Sihir Gadget
Seolah sabda nabi yang pasti benarnya. Kebebalan dan keengganan kita dalam memverifikasi berita, memudahkan kebohongan menyelinap masuk. Membuat kita tak mampu membedakan mana berita, opini, fakta dan analisis. Medsos sebagai bentuk jurnalisme warga ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoax. Menjadi sumber ketegangan dan konflik.
Seolah berita di medsos yang viral adalah saudara kembar kita. Kita berempati dan menyatu dengan informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Dan informasi dengan derajat “seolah benar” di medsos tersebut, diyakini dengan fanatik. Dibela habis-habisan. Maka cara pandang pun terpolarisasi. Yang berbeda dimusuhi, dihujat, dicaci maki dan “diadili” di medsos.
Orang yang seperti ini terkena sindrom ilusi Müller-Lyer, Franz Carl Müller-Lyer (1857-1916), orang Jerman ini menyatakan bahwa opini atau ideologi yang dimiliki atau dipilih seseorang dan dianggap sebagai kebenaran, akan sulit untuk digeser apalagi diubah. “Keukeuh” dengan pendapatnya! Jargonnya adalah “pokoe”.
Seperti hanya pluralitas sebagai sebuah realitas, disangkal untuk diseragamkan karena polarisasi keyakinan, ideologi, politik dan kepentingan. Melahirkan perseteruan dan tak bisa menerima kebenaran dari pihak lain. Inilah yang disebut sindrom ilusi Müller-Lyer, ilusi kebenaran pada pandangan seseorang.
Tidak hanya ‘keukeuh”, pengidap ilusi Müller-Lyer juga menolak pandangan yang berbeda. Orang yang terkena sindrom Müller-Lyer cendrung mengabaikan fakta obyektif apa pun dan tetap tidak mengubah pandangan, opini atau keyakinananya. Bahkan argument yang didasarkan pada penalaran rasional nan cangih pun, akan ditolak!
Ciri orang-orang yang terkena sindrom Müller-Lyer, penalaran lebih berfungsi untuk pembenaran apa yang diyakininya. Sehingga tak sungkan dan mudah berbohong atau menipu, untuk menutupinya. Bahkan dirinya sendiri percaya kebohongannya adalah kebenaran. Bagi orang yang terkena sindrom ini, melakukan kebohongan dan menipu, tak lagi melahirkan rasa salah. Sebab kebohongannya yang diviralkan, diyakini sebagai kebenaran oleh orang lain, pun dirinya.
Pantas jika J.A. Llorente menyebutnya, saat ini era Post-Truth. Hasrat dan emosi lebih memihak kepentingan/ keyakinannya dan lebih dominan dibanding obyektivitas dan rasional.
Meskipun sebenarnya fakta berbanding terbalik alias berbeda. Melahirkan tsunami kebohongan dalam sistem komunikasi di medsos. Dan sekaligus kebebalan nalar kritis untuk cek dan ricek, berita atau informasi di medsos. (Kang Marbawi, 110125)